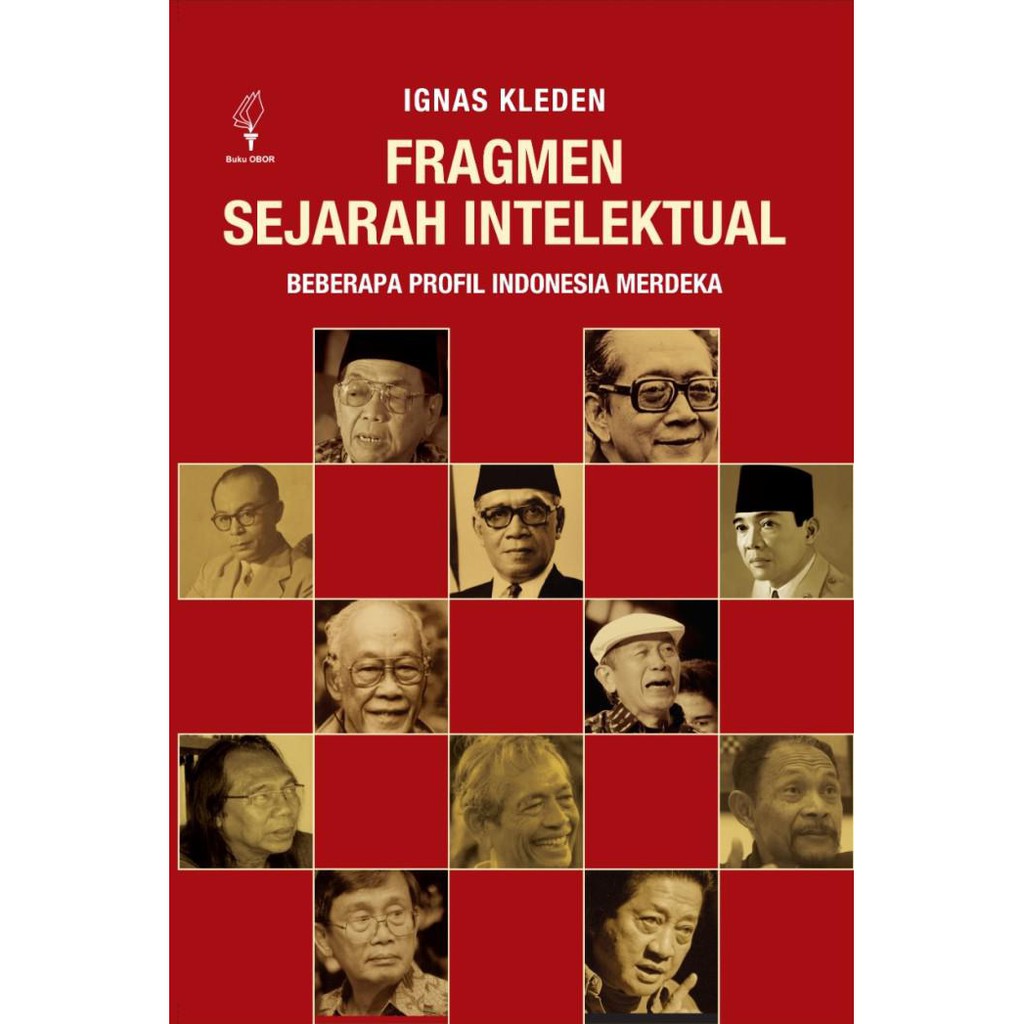 Judul: Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka
Judul: Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka
Penulis: Ignas Kleden
Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Desember 2020
Tebal: xii + 460 halaman
ISBN 9786024336875 (paperback)
Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka merupakan sebuah antologi, atau kumpulan karya yang disusun dan dipilih oleh penulisnya, Ignas Kleden. Setiap bab merupakan penerbitan ulang karya penulis pada surat kabar Kompas, majalah berita mingguan Tempo, jurnal Prisma. Ketiga media cetak itu, “… telah banyak berjasa mengumumkan esai-esai kebudayaan, sosial-politik dan ilmu-ilmu sosial, yang beberapa dari antaranya terbit kembali dalam buku ini” (hal. xi). Penerbit LP3ES dan Dian Rakyat juga disebut karena beberapa buku kedua penerbit ini memuat kajian penulis tentang pemikiran Soedjatmoko dan Sutan Takdir Alisjahbana. Tulisan lain tentang visi dan kritik kebudayaan Pramoedya Ananta Toer juga pernah menjadi bahan ceramah di Pusat Kesenian Salihara, Jakarta. Penyusunan dan pengumpulan kembali tulisan-tulisan itu didukung oleh Freedom Institute (hal. xii). Tinjauan ini disusun dengan pengetahuan bahwa karya ini bukanlah monograf (buku) yang memiliki pertanyaan sentral, yang dijawab melalui koherensi antar-bab. Karena itu, tulisan ini merespons logika penulis dalam melakukan seleksi karyanya.
Antologi ini diorganisasi menjadi dua bagian. Bagian pertama bertajuk “Tokoh-tokoh Pemikir Politik Indonesia,” memuat sejumlah nama seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Soedjatmoko, Frans Seda, Abdurrahman Wahid, dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sementara itu, bagian kedua berjudul “Pemikiran tentang Sastra dan Kebudayaan”, yang mencakup Sutan Takdir Alisjahbana, Ajip Rosidi, Asrul Sani, Mochtar Lubis, WS Rendra, Goenawan Mohamad, Putu Wijaya, Sutardji Calzoum Bachri, Sardono W Kusumo, dan Jakob Oetama, dengan gaya penulisan lebih bebas dibandingkan bagian pertama.
Sebagaimana disampaikan pada paruh antologi ini yang berjudul “Atas Nama Apologia,” penulis memberikan penafian (disclaimer) bahwa ada beberapa kekurangan tak terhindarkan. Di antaranya, antologi ini “tidaklah ditulis dengan mengkuti suatu rencana yang utuh, melainkan lahir dari berbagai kesempatan dan keperluan yang bersifat ad hoc” (hal. vii). Karena itu, barisan intelektual Islam, perempuan, kalangan Kristen, dan lainnya luput dari pembahasan. Dengan pertimbangan itu, saya mengorganisasi tinjauan ini sebagai sebuah respons atas permintaan penulis:
“Penulis ingin menekankan bahwa buku ini dalam bentuk antologi, lebih merupakan sebuah percobaan, karena sejarah intelektual belum merupakan pengertian yang baku secara akademis, seperti sejarah filsafat, sejarah pemikiran, sejarah teori politik atau teori ekonomi atau sejarah dogma, dan sejarah teologi. Pengertian sejarah intelektual itu semakin dipersulit karena pengertian intelektual sebagai perorangan atau sebagai kelompok juga masih penuh dengan diskusi dan kontroversi…. Penulis berharap uraian berdasarkan data sejarah itu, lebih menjelaskan siapa itu intelektual, daripada memberikan suatu konsep atau bahkan definisi tentang siapa itu intelektual (hal. ix-x).”
Pada bagian pengantar antologi, penulis mengurasi definisi intelektual dan ilmuwan abad ke-19 dan ke-20, seperti Edward Said (1996), Antonio Gramsci (1983), Tenas Effendi (1997), Georg WF Hegel (1970), Matthrew Arnold (1882), George Orwell (1981), Soedjatmoko (1996), Jean-Jacques Rousseau (1923), Bertrand Russel (1981), Will Durant dan Ariel Durant (1982), Ralph Waldo Emerson (1950), Joseph L Blau (1966), Adam Smith (1957), Thomas Paine (2003), Frederick Mayer (1951), Immanuel Kant (1995), Alfred North Whitehead (1925), Jean L Cohen dan Andrew Arato (1994) (hal. 1-29). Namun, sepanjang membaca tulisan-tulisan ini, saya sulit mencari jangkar atau kerangka pemikiran yang lazim ditemukan dalam setiap antologi atau buku suntingan (edited book). Saya kemudian mengambil keputusan bahwa jangkar akademis tidak perlu dicari, karena penulis tidak sedang menulis sebuah “buku” melainkan antologi, sehingga pemikiran sarjana abad ke-19 dan ke-20, sebagaimana setiap bab yang disajikan dalam “buku” ini, merupakan hasil kurasi penulis. Walaupun tidak disebut secara konkret, penulis mengurasi intelektual Indonesia dalam cakupan sejarah abad ke-20. Kondisi historis dan uraian konteks diperinci dan tersemat dalam tiap petikan dengan cara sastrawi. Dengan kata lain, antologi ini dapat dibaca dengan apresiasi yang sesuai dengan gaya yang penulis pilih.
Kurasi, sebagaimana dilakukan untuk barang-barang seni, adalah upaya merakit, mengelola, dan menyajikan koleksi untuk mengawasi interpretasi dan menyajikan eksibisi. Bagi saya, penulis berpikir dalam koridor yang telah dia tetapkan dan mengartikulasikannya sejak awal. Ignas Kleden juga setia dan konsisten pada kurasinya. Lebih jauh, penulis menginterpretasikan dan membandingkan tugas seorang ilmuwan dengan yang dilakukan oleh seorang intelektual publik:
“Menurut pendapat saya, seorang intelektual juga bekerja dengan informasi dan pengetahuan, tetapi dia tidak menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai tujuan kerjanya, melainkan sebagai sarana, sebagai jalan, sebagai fasilitas. Seorang ilmuwan mengubah kepercayaan dan nilai menjadi informasi dan pengetahuan, sementara seorang intelektual mengubah pengetahuan dan informasi menjadi nilai, komitmen politik, keyakinan ideologis atau sikap moral. Seorang ilmuwan membatasi kerjanya dalam disiplin yang menjadi bidang keahliannya, sementara seorang intelektual menerobos disiplin keilmuannya, karena tujuan yang menggerakkan dia bukanlah suatu arsitektur pengetahuan yang harus dibangunnya, melainkan suatu masalah publik yang harus dipikirkan dengan segera, atau kepentingan publik yang harus diselamatkan atau dibela (hal. 12).”
Walaupun memberi definisi teoretis mengenai siapa itu ilmuwan dan intelektual bukan tujuan penulis, pendapat Ignas Kleden mengingatkan saya akan perdebatan akademis mengenai ilmu sosial dan yang telah dilakukan oleh Michael Burawoy sejak awal abad ke-21.[1] Pada saat yang sama, Burawoy berinteraksi dengan dan direspons oleh banyak sarjana sebagai bagian dari sistem sosial yang juga dijelaskan Ignas Kleden dalam antologi ini. Dia dikritik, didebat, ditantang, dan dilengkapi dengan, setidaknya, teori intersectionality,[2] teori complexity,[3] dan juga pendekatan etnografi,[4] yang berargumen bahwa selalu ada hal terperinci yang luput dari analisis makro yang dapat diisi oleh penelitian mikro dan keseharian.
Penulis mengurasi kerja intelektual sebagai sebuah aksi dari beberapa pemikir. Misalnya, dia merujuk Hannah Arendt yang berpendapat bahwa “kekuasaan bukanlah kemampuan memaksakan kehendak kepada perilaku orang lain,[5] karena kekuasaan tidak berasal dari kemampuan seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu, melainkan dari kesanggupan seseorang untuk mencapai kesepakatan dengan orang lain untuk bertindak secara bersama” (hal. 58). Sementara itu, mengutip Talcott Parsons, Kleden “menekankan pentingnya suatu sistem sosial dan adanya tujuan kolektif dalam sistem sosial …. kekuasaan tidak lain dari kemampuan suatu sistem sosial untuk memobilisasi sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif” (hal. 58-59). Parsons mendefinisikan kekuasaan (power) sebagai the capacity of a social system to mobilize resources to attain goals.[6] Menurut Kleden, definisi Parsons tentang kekuasaan berbeda dengan definisi Max Weber, tetapi memiliki penekanan yang sama pada realisasi suatu tujuan. Max Weber berangkat dari teori tindakan sosial, sedangkan Parsons bertolak dari teori sistem sosial (hal. 59).
Penulis tidak secara eksplisit mengambil posisi akademik mengenai kerja ilmuwan dan intelektual sebagai aksi atau sebagai bagian dari sistem sosial sepanjang antologinya. Meskipun demikian, penulis mengurasi Sukarno (2003), Tan Malaka (2000), M Natsir (2001), M Hatta (1998), Ki Hajar Dewantara (1962), Goenawan Mohamad (2011), Ajib Rosidi (2008), Mochtar Lubis (2009), Kartini (1992), dan melengkapi mereka dengan studi Indonesianis yang berbasis di Amerika Serikat, seperti Audrey R Kahin (2012) dan Cindy Adams (1986). Bagi saya, pada praktiknya penulis mengambil posisi akademik yang eklektik dan kuratorial.
Lebih lengkapnya lagi, penulis menyeleksi dan mengorganisasi tokoh pengetahuan dalam beberapa imajinasi sejarah. Yang pertama adalah imajinasi tentang sejarah pasca-kemerdekaan dan yang kedua adalah imajinasi mengenai sejarah pembangunan. Kedua imajinasi intelektual itu tersedia di bagian pertama buku, sementara bagian kedua memiliki keberagaman yang amat tinggi, sehingga lebih sesuai jika direspons sebagai kumpulan karya sastra reflektif atau, meminjam istilah pascamodernis, sebuah hodgepodge. Imajinasi sejarah dalam antologi ini tampak pada kutipan berikut:
“Perkembangan baru muncul sejak awal abad 20 dengan munculnya kaum terpelajar pribumi, berkat Pendidikan Barat yang mereka peroleh dari sekolah-sekolah Belanda, oleh dorongan Politik Etis yang diperjuangkan oleh kaum liberal di belanda. Merekalah, kaum terpelajar ini, yang mengambil alih kepemimpinan dalam perjuangan melawan penjajahan, dan menerjemahkan perjuangan bersenjata abad ke-19 menjadi perjuangan politik dalam pergerakan politik dan partai-partai politik sebagai hal baru yang tidak dapat dicap begitu saja sebagai ilegal dalam hukum kolonial” (hal. 61).
Namun, karya seminal Benedict R’OG Anderson yang mengkaji gerakan intelektual muda di Hindia-Belanda yang juga penulis paparkan pada antologinya, tidak disebut.[7] Padahal, buku Ben Anderson itu secara paradigmatik memengaruhi perdebatan mengenai teori nasionalisme sebagai konstruksi sosial hingga hari ini. Selain itu, buku Andrew Goss yang menginvestigasi secara tajam hubungan antara sains, negara, dan masyarakat di Indonesia modern, juga tidak disentuh.[8] Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, saya menyadari bahwa antologi dan kurasi tokoh pengetahuan abad ke-20 Indonesia dilukiskan dari kesaksian berbasis aksi Ignas Kleden, seorang cendekiawan Flores Timur yang berperan sentral dalam kritik kebudayaan masa Orde Baru dan awal Reformasi. Dengan kesadaran ini, pembaca dapat menempatkan antologi sebagai praktik cendekia di Kepulauan Melayu pascakolonial, yang mewarnai secara tidak langsung gambaran global perdebatan akademik di “Global South.” Hal itu juga terlihat pada, yang kedua, imajinasi sejarah pembangunan dalam antologi, khususnya dalam bab mengenai Soedjatmoko.
“Kalau kita menggunakan ikhtisar modernisasi … maka dapat pula diajukan suatu ikhtisar pembagian kerja antar-ilmu dalam menghadapi masalah modernisasi. Kalau masalah pertumbuhan dapat dianggap sebagai masalah ilmu ekonomi, dan kalau social engineering dapat dianggap menjadi urusan ilmu sosial, maka pembangunan dapat dianggap lebih merupakan masalah etik politik. Dengan demikian, pemikiran Soedjatmoko sebagian besarnya bergerak antara ilmu sosial dan filsafat sosial. Posisinya ini akan bertambah jelas kalau kita ingat akan pernyataannya tentang perlunya teori sosial yang dapat menjadi pedoman untuk merancang teori-teori pembangunan, dan kritiknya terhadap ketidakmampuan ilmu sosial menghadapi masalah pembangunan, baik dalam rendahnya daya eksplanasi maupun dalam rendahnya efektivitas untuk melakukan social engineering” (hal. 174-175).
Pada bagian itu, saya memaklumi bahwa antologi ini secara implisit memberikan kisah kesarjanaan (academic storytelling) yang sejalan dengan perkembangan sejarah pada momen ia ditulis. Meskipun penulis tidak menghubungkan pemikiran para tokoh pengetahuan Indonesia tahun 1980-an dengan perdebatan global mengenai pembangunanisme (developmentalism), saya memilih menyikapi antologi ini sebagai aksi intelektual penulis. Dengan demikian, bagian kedua buku yang dikurasi dengan cara lebih eksploratif dibandingkan bagian pertama lebih masuk akal. Sebagaimana Kleden artikulasikan dalam bab mengenai sebuah buku yang ditulis oleh Jakob Oetama:[9]
“‘Refleksi’ adalah sebuah kata kunci dalam buku ini, dan karena itu sebaiknya istilah ini sedikit dijabarkan pengertiannya secara lebih luas. Dalam kalangan ilmu-ilmu sosial positivis, istilah refleksi tidak dikenal. Ini pula sebabnya, ilmu-ilmu sosial yang mengambil alih metode-metode ilmu alam dan menerapkannya begitu saja dalam bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan, kemudian dituduh sebagai positivis. Alasannya, ilmu-ilmu sosial sejenis ini bisa mengamati, menguraikan, dan mengkritik segala sesuatu yang menjadi obyek studinya, tetapi tidak pernah sanggup mengamati, menguraikan dan mengkritik dirinya sendiri, berupa asumsi-asumsinya, nilai-nilai yang membentuk asumsinya, maupun kecenderungan ideologis yang secara diam-diam memengaruhi pembentukan teori-teorinya” (hal. 401).
Kritik tajam penulis mengingatkan saya akan dua buku dengan para penulisnya mengamati, menguraikan, dan mengkritik sarjana (tentu termasuk dirinya) dalam sistem sosial yang sarat kekuasaan, namun tidak dirujuk penulis antologi ini. Buku yang pertama ditulis oleh Daniel Dhakidae berjudul Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, sedangkan yang kedua disunting Daniel Dhakidae dan Vedi R Hadiz berjudul Social Science and Power in Indonesia.[10] Dua buku itulah yang mengenalkan dan menghubungkan saya, sebagai seorang sarjana kampus di Indonesia yang mengkaji, menulis, dan memiliki praksis intelektual publik (dalam logika Burawoy) secara multi-skalar (lokal, nasional, global) pada lingkungan sosial (social milieu) akademis antargenerasi dan interseksional (antara kampus dengan gerakan, antar-isu dan mawas periode sejarah). Absen dalam antologi itu juga adalah beberapa sarjana seminal di abad ke-21, setidaknya bagi generasi saya, seperti Arief Budiman, Ariel Heryanto, Hilmar Farid, Melani Budianta, yang bukan saja antara praksis dan intelektualitasnya tidak terpisah, tulisan dan karya-karya mereka memengaruhi cara intelektual di Asia Pasifik memahami Indonesia.
Membaca antologi ini dengan kritis menawarkan ruang refleksi, baik bagi ilmuwan sosial maupun intelektual yang bukan merupakan bagian langsung dari lingkungan sosial penulis. Dengan demikian, antologi ini dapat direspons oleh sidang pembaca dengan kemauan untuk mematut diri dalam sistem pengetahuan global yang lebih luas.[11] Berhubung antologi ini disusun dari lingkungan sosial yang spesifik, ia hanya akan berdampak ke diskusi akademis global jika pembaca menempatkannya dalam khazanah yang lebih luas.
Hal demikian membuka kesempatan bagi para pembaca dan penulis lain untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru. Misalnya, apa dan siapa ilmuwan dan intelektual Indonesia di abad ke-21? Bagaimana dampak marketisasi gelombang ketiga terhadap proses kerja kesarjanaan? Bagaimana transformasi digital dan intensifikasi proses kerja imaterial (melalui digitalisasi) mengubah aksi intelektual publik? Bagaimana perubahan iklim memaksa ilmuwan dari tradisi ilmu lingkungan, geologi, meteorologi, dan kesehatan, berinteraksi dengan intelektual dari tradisi keilmuan sosiologi, antropologi, gender, politik, dan sebagainya? Siapa yang mendefinisikan “Indonesia” dalam perkembangan kesarjanaan mengenai Indonesia? Bagaimana posisionalitas sarjana diaspora dan dampaknya pada gerakan sosial mengenai dan Indonesia? Terakhir, yang paling penting, bagaimana semua kerja akademis kita dapat bermanfaat bagi mereka yang paling rentan?
Sebenarnya, setidaknya bagi saya, yang dilakukan Ignas Kleden melalui antologi ini turut memberi warna bagi mozaik yang berangsur-angsur dan secara ekstensif dilengkapi oleh akademisi di Global South. “Refleksi” atau kemampuan menyadari dan mengurai proses sosial yang membentuk asumsi-asumsi teoretis kita yang ditekankan penulis antologi ini secara mendasar serupa dengan begitu banyak upaya akademisi ilmu sosial lainnya yang menjadi bagian dari gerakan intelektual pascakolonial dan pasca-otoritarian. Ignas Kleden melakukan hal itu dengan mendefinisikan ilmu sosial dan intelektual dari sudut pandang dan konteks sosialnya, yaitu dari momen sejarah formatif abad ke-20. ●
Catatan akhir:
[1] Lihat, Michael Burawoy, “For Public Policy,” dalam American Sociological Review, Vol. 70, No. 1, 2005, hal. 4-28; Michael Burawoy, “Rejoinder: For a Subtaltern Global Sociology?” dalam Current Sociology, Vol. 56, No. 4, 2008, hal. 435-555; Michael Burawoy, “Redefining the Public University: Global and National Contexts,” dalam John Holmwood (ed.), A Manifesto for the Public University (London: Bloomsburry, 2011), hal. 27-41.
[2] Lihat, Patricia Hill Collins dan Sirma Bilge, Intersectionality (Key Concept 2nd Edition) (Cambridge, UK: Polity Press, 2020).
[3] Lihat, David Byrne dan Gillian Callaghan, Complexity Theory and the Social Sciences: The State of the Art (London: Routledge, 2013.
[4] Lihat, Paul Atkinson, Ethnography: Principles in Practice (London: Routledge, 2007).
[5] Lihat, Hannah Arendt, The Human Condition (Garden City-New York: Doubleday Anchor Book, 1959).
[6] Lihat, Talcott Parsons, Structure and Process in Modern Societies (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1960), hal. 181.
[7] Lihat, Benedict RO’G Anderson, Imagined Communities: Reflctions on the Origin and Spread of Nationalism (London & New York: Verso Books, 2006).
[8] Lihat, Andrew Goss, The Floracrats: State-sponsored Science and the Failure of the Enlightenment in Indonesia (Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2011).
[9] Lihat, Jakob Oetama, Pers Indonesia; Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
[10] Lihat, Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003); Daniel Dhakidae dan Vedi R Hadiz (eds.), Social Science and Power in Indonesia (Jakarta: Equinox, 2005).
[11] Untuk perbandingan peta publikasi di “Global South” dan “Global North”; lihat, Fran Collyer, “Global Patterns in the Publishing Academic Knowledge: Global North, Global South,” dalam Current Sociology, Vol. 66, No. 1, 2018, hal. 56-73. Untuk keterbatasan dekolonisasi intelektual; lihat, Leon Moosavi, “The Decolonial Bandwagon and the Dangers of Intellectual Decolonisation,” dalam International Review of Sociology, Vol. 30, No. 2, 2020, hal. 332-354. Untuk isu keberagaman dalam ilmu sosial; lihat, Benjamin Baez, “The Study of Diversity: The ‘Knowledge of Difference’ and the Limits of Science,” dalam The Journal of Higher Education, Vol. 75, No. 3, 2004, hal. 285-306.